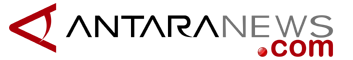Sebagai penggemar hal-hal lucu-lucu, dan tentu saja “fans berat” Srimulat (sayang kelompok lawak ini tampaknya hanya “tinggal kenangan”), saya merasa cukup terhibur oleh pembawaan Butet dalam melempar kritik-kritik lucu tapi getir itu.
Lucu, karena ia mencoba menarik kejadian-kejadian aktual ke dalam lawakannya, getir karena, lelucon Butet secara gamblang itu rasa-rasanya (setidaknya ada yang merasakan begitu) seperti menampar muka sendiri.
Otokritik memang selalu membuat kita butuh mentalitas tersendiri untuk mempersiapkannya. Dan, banyak yang tak siap dengan lelucon Butet itu.
Bagi saya sih, senang-senang saja dengan hiburan itu, setidaknya membuat mimik menjadi tersenyum dan tertawa. Itu artinya urat-urat “awet muda” teraktifkan.
Katanya, kalau kau awet muda, banyak-banyaklah tersenyum dan juga “tertawa”, daripada marah dan cemberut alias dalam bahasa Butet yang dari Yogya “njegadul”.
Saya kira, Butet tampil di acara itu atas undangan KPU dan karenanya ia ditampilkan oleh KPU sebagai karikatur hidup. Artinya Butet tampil seperti Oom Pasikom-nya GM Sudarta di Harian Kompas. Ketika Butet menyindir KPU, saya masih “angkat topi”.
Tetapi giliran ia berkisah tentang bajunya Mas Prabowo Subianto (bukan kudanya), dan mengabarkan bahwa ia seorang pemimpin yang siap mengambil jalan kesederhanaan, maka saya menunggu giliran tokoh-tokoh lain disebut. Tapi, tak berapa lama Butet mengakhiri monolognya.
Setelah itu saya baru tahu bahwa putera almarhum Bagong Kusudiardjo ini, mewakili pasangan Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Mega-Pro). Dan lantas muncul pro-kontra.
Saya membayangkan Butet sendiri, hanya senyum-senyum dengan kemunculan berbagai pro-kontra mengenai aksinya malam itu. Butet telah memberikan suatu interupsi kontroversial. Melalui berbagai komentar yang mengemuka di media massa kubu pasangan SBY-Boediono menyesalkan atraksi Butet itu sebagai sesuatu yang provokatif.
Tetapi, kubu Mega-Pro dan kubu pasangan Jusuf Kalla (JK) – Wiranto, cenderung tak mempersoalkannya, mengingat “incumbent” harus siap dikritik. Sampai tulisan ini di tulis, pro-kontra masih terus berlanjut pasca-Deklarasi Pemilu Damai itu.
Bagaimana dengan pihak KPU sendiri? Ada pendapat yang bernada menyesalkan,
misalnya dari Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari, bahwa mestinya dalam deklarasi tak usah menyinggung yang lain. Ada juga yang lebih lunak, misalnya yang disampaikan Andi Nurpati, yang lebih menekankan bahwa atraksi Butet itu netral saja, memang banyak tafsir tetapi hiburan biasa saja.
Saya sendiri berharap ini merupakan suatu pelajaran, bahwa kita suka kritik, dan apa yang disampaikan Butet itu kritik yang baik (kecuali bagian yang “memuji” baju Mas Prabowo), karenanya saya berpikir bilamana kelak KPU mengundang Butet dalam posisinya sebagai seniman independen, tampil sebagai monolog-kritis tetapi kehadirannya bukan mewakili kandidat atau partai politik tertentu. Kalau perlu ada Butet-Butet lain, biar kritiknya dari berbagai perspektif dan “checks and balances”.
Kritik dan Politik
Jarak antara kritik dan politik, sesungguhnya sangat dekat. Kritik itu banyak disampaikan melalui beragam ekspresi dan media. Gaya penyampaiannya merentang dari yang halus-sinis hingga kasar-sarkastik.
Kritik itu seperti obat, dan sebagaimana juga Butet Kertaredjasa pernah tampilkan dalam monolognya “Matinya Toekang Kritik”, para kritisi tak boleh mati di bawah rezim apa pun. Tempo dulu, sewaktu kita masih dalam pemerintahan Orde Baru, ketika rezim sensitif sekali dengan kritik, pernah ada buku populer judulnya “Mati Ketawa a la Rusia”. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memberikan kata pengantarnya, bahwa otoritarianisme bisa dilawan dengan tertawa.
Banyak juru kritik mati di tiang gantungan rezim otoriter, ada juga yang lolos melarikan diri ke luar negeri, seperti yang dialami oleh sastrawan pemenang Nobel Rusia Alexander Solzhenitsyn. Di negara-negara Barat banyak kritikus satir yang terus dikenang, sebagai seniman yang kritikannya mewakili sebagian besar perasaan masyarakat, misalnya ketika sastrawan Inggris Goerge Orwell menulis “Animal Farm” pada akhir masa Perang Dunia II.
Kritikus-kritikus lain yang terkemuka antara lain, Boris Pasternak dari Rusia, atau Cak Durasim dari Surabaya.
Cak Durasim adalah kritikus agung yang menyuarakan aspirasi masyarakat anti-kolonial, anti-penjajahan Jepang dengan syair-syair ludruknya. Saya masih ingat bunyi syair legendaris Cak Durasim, seniman yang melampaui Cak Kartolo cs masa sekarang itu, begini: “pagupon omahe doro, melok Nippon tambah soro”.
Pagupon (ada yang menulis “begupon”) rumahnya burung dara (merpati), ikut Nippon (Jepang) tambah sengsara. Orang seperti Cak Durasim ini sangat berbahaya bagi rezim pendudukan Jepang. Saya tidak tahu apakah lantas ia ditangkap dan dieksekusi. Yang jelas untuk mengenangnya, patungnya telah terpampang sekarang di depan Taman Budaya Jawa Timur di Surabaya.
Pada masa reformasi ini, saya setuju, masih diperlukan Cak Durasim-Cak Durasim baru, juga Butet-Butet lain, asal diberikan ruang dan proporsi yang tepat, kalau perlu “dilembagakan”. Masyarakat akan menjadi elemen kontrol atas kebebasan berekspresi, dan yang di luar proporsi, saya kira akan menuai kontroversi yang bertele-tele, seperti yang terjadi pada Butet saat ini.
Para capres saja saling sindir itu biasa, apalagi para seniman. Kalau seniman berpolitik, yang penting identitasnya jelas, mewakili siapa. Dalam kasus Butet, ia tak sepenuhnya dapat disalahkan. Identitas Butet jelas: wakil Mega-Pro. Walaupun penikmat lelucon seperti saya terpaksa sedikit protes, mengapa Butet tak independen saja.
Otokritik memang pahit, tapi seperti jamu, kritik itu perlu, supaya kita tumbuh menjadi bangsa yang sehat dan dewasa, juga inspiratif dan berbesar jiwa. Wallahua’lam. (*)
* Penulis adalah seorang pengamat politik dari Universitas Nasional, Jakarta
Oleh Alfan Alfian
Editor: Anton Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2009