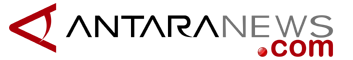“Suara Obama terasa lantang di tengah senyapnya suara perbincangan tentang makna Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat toleransi di kalangan masyarakat Indonesia sendiri, lebih-lebih belakangan ini”, demikian ulasan tajuk satu koran di Jakarta. Selain itui, semua kegiatan Obama di Indonesiajuga disaksikan jutaan pemirsa televisi di dalam dan luar negeri,
Pada peringatan 61 tahun lahirnya Pancasila, 1 Juni 2006, di Balai Sidang Jakarta (Jakarta Convention Center/JCC). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan perasaannya
"Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, stabilitas, pembangunan, kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis," ujar SBY.
Pada waktu itu ada 17 tokoh nasional dari bebagai unsur, antara lain Jakob Oetama, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad dan Rahman Tolleng juga mendeklarasikan “Maklumat Ke-Indonesiaan".
“Peringatan ini dilakukan atas dasar kerisauan akan tanggalnya visi bangsa ke depan dan menipisnya rasa kekitaan sebagai Indonesia yang majemuk, berbeda tetapi tetap satu”, kata Prof DR Gumilar R. Soemantri, yang menjadi ketua panitia acara tersebut.
Orkestra
Apa yang terjadi selama kurun masa 2006 sampai 2010 ini? Masyarakat luas dapat menyaksikan bahwa sangat tidak menghendaki pemandangan murung, dan ketidakberdayaan rakyat kecil melalui liputan media yang bertubi-tubi disiarkan setiap hari.
Melalui layar televisi, utamanya, terangkat pesan-pesan kekerasan ke dalam bilik-bilik keluarga Indonesia, yang di kaki gunung sekalipun. Isinya nyaris menutupi pesan-pesan kebajikan sejenis “Kuliah Subuh”.
Masyarakat ibarat dipaksa menyaksikan beberapa potong pemandangan memilukan atas ketidakberdayaan rakyat kecil. Seolah-olah kue keadilan hukum dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan janji konstitusi, belum sempat dinikmati.
Topiknya berputar-putar antara nasib kelam pedagang kaki lima, perampasan lahan dan bangunan untuk mal dan apartement mewah, pemenjaraan rakyat kecil, kerusuhan pertunjukan konser musik ataupun pertandingan sepakbola. Bahkan, ada wajah tersenyum oknum pejabat yang terlibat kasus korupsi.
Perhatian publik juga dihiasi rentetan bencana alam, seperti longsor, banjir, gempa bumi, tsunami dan letusan gunung, menyebar di seluruh negeri. Istilah kata, nyaris sempurna penderitaan rakyat Indonesia.
Orkestra yang memilukan hati bangsa ini, jika dibiarkan, maka akan menimbulkan frustrasi sosial. Peragaan perilaku sebagian pemimpin bangsa yang kurang terpuji lama-kelamaan dapat membuat bangsa terjebak dalam situasi destruktif: disorientasi.
Paradigma baru
Pemerintah selaku penyelenggara negara telah membuat serangkaian kebijakan untuk mengatur lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Isinya sudah dilandasi jiwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, rakyat masih sering menyaksikan --terutama melalui multimedia massa-- dua pusat kekuasaan, yakni Istana (eksekutif) dan Senayan (legislatif) terkadang bersimpang arah. Di satu sisi, dua kutub penyelenggara negara ini lebih sering di dalam polemik politik yang berkadar subyektivitas sektoral.
Di sisi lain, dua kutub tersebut seringkali berpadu langkah. Eksekutif dan legislatif seiring sejalan, namun meninggalkan aspirasi rakyat di luar Istana dan Senayan. Tidak jarang muncul ketegangan di antara keduanya dalam hal-hal tertentu, justru atas nama kepentingan rakyat.
Masyarakat yang kecewa akhirnya ada yang menempuh cara parlemen jalanan. Model kerumunan yang gampang mendapat liputan media. Dominasi bahasa politik yang ditempuh selama ini terasa kurang memberi pencerahan.
Selain banyak menguras energi, sering terjebak dalam wacana sangat teknis dan dangkal. Wacana lebih banyak membuka ruang rivalitas partisan, yang menciptakan luka kebangsaan. Bahkan, ada yang “mengikis kekitaan kita” layaknya yang pernah disinggung oleh Prof DR Goemilar R. Soemantri.
Bangsa Indonesia perlu menggagas kesepakatan paradigma baru, konsensus nasional. Bertumpu kepada penghormatan atas apa yang telah menjadi pilihan rakyat, yang terlegitimasi melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).
Presiden dan legislator yang dipilih langsung oleh rakyat pada tempatnya dihargai. Sebagai bentuk penghormatan kepada kedaulatan rakyat. Sebaliknya, Presiden dan legislator yang terhormat pun seyogyanya menghargai dan menjaga amanat rakyat.
Presiden tentu saja selalu diharapkan rakyatnya harus membuka diri, berdialog maraton dan komprehensif dengan segenap komponen bangsa. Ini sebagai upaya reaktualisasi dan memperbarui aspirasi rakyat yang bergerak dinamis. Dengan cara seperti itu, maka presiden akan menerima variasi masukan untuk mengimbangi nada tunggal dan masukan monoton dari internal Istana.
Para legislator demikian juga. Mereka harus secara kolektif menolak godaan menjadi aktor utama praktik pragmatsime dan perilaku transaksionalisasi. Mereka harus menjauhi perilaku yang beraroma kepentingan pribadi, melukai hati rakyat. Senandung lagu wakil rakyat ala Iwan Fals harus tercermin dalam paket satunya sumpah dan langkah mereka.
Kontemplasi
Komponen bangsa ini harus sepakat mencegah jangan sampai nilai fundamental kebangsaan terdegradasi oleh pergulatan subyektivitas “warna bendera” parpol. Bagaimana pun, di negeri ini harus ada kesepakatan mengakhiri kekacauan. Bangsa ini perlu melakukan perenungan kolektif, semacam kontemplasi nasional.
Kapal induk yang bernama Indonesia harus diselamatkan. Atas dasar semangat egaliteritas. Hambatan yang merintangi proses untuk meng-Indonesia selama ini ditengarai karena suburnya perilaku egosentris kekuasaan. Hal ini jika dibiarkan, maka lambat laun akan memupuk kekuatan perlawanan di luar pemerintah. Pada akhirnya: simbol negara berhadapan dengan warganegara!
Sebaliknya, model kerumunan yang merebak untuk merespons kelemahan negara harus diwaspadai lebih jauh antara mudarat dan manfaatnya. Kerumunan hanya akan berujung kepada munculnya kerumunan tandingan. Niat baik membersihkan kutub kekukasaan dari elemen “makelar kekuasaan” dan “petualang politik” tidak efektif jika hanya mengandalkan kerumunan. Kerumunan yang sporadis pasti akan dikalahkan oleh kejahatan yang terkonsolidasi.
Presiden Obama memang tidak seideologi dengan bangsa Indonesia. Namun, sebagai "bekas anak Menteng" yang ibundanya (Ann Dunham, warga AS) adalah peneliti kebudayaan Indonesia dan berayah tiri (Lolo Sutoro Mangunhardjo, warga RI) seorang demograf juga geolog, maka tak mengherankan manakala ada bagian-bagian yang mencerahkan dari pidatonya tentang ketangguhan Bhinneka Tungal Ika dan Pancasila sebagai perekat kebangsaan.
Semangat Obama juga mewakili keinginan bangsa Indonesia. Paling tidak, gemuruh, sorak sorai dan tepuk tangan pengunjung pidatonya di UI bisa jadi bukti. Ini perlu kita bawa dalam mimpi setiap kali berangkat tidur. Jangan sampai kedua nilai luhur bangsa --Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-- kita biarkan tertidur. Kita semua harus tersadarkan. Indonesia sedang bergegas!
*) Zainal Bintang (bintang1246@yahoo.com) adalah wartawan senior; pemerhati kebudayaan.
Oleh Zainal Bintang *)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2010