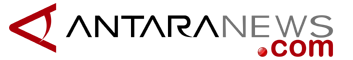Realpolitik adalah konsepsi politik yang dicetuskan politisi Jerman abad ke-19 bernama Ludwig von Rochau.
Konsepsi ini awalnya untuk politik domestik, namun berubah menjadi konsep yang dikenal baik dalam teori maupun praktik politik internasional.
Henry Kissinger, menteri luar negeri Amerika Serikat era 1970-an, mendefinisikan realpolitik sebagai "kebijakan luar negeri yang didasarkan kepada kalkulasi kekuatan dan kepentingan nasional."
Tetapi teorisi hubungan internasional terkenal, Kenneth Waltz menyebut realpolitik "metode dalam mana kebijakan luar negeri diterapkan sehingga semua hal menjadi terlihat rasional."
Sederhananya, realpolitik adalah tindakan politik yang lebih didasarkan kepada pertimbangan praktis ketimbang moral atau ideologi. Dalam kata lain, pragmatisme.
Waltz menyebut konsepsi ini sama tuanya dengan sejarah umat manusia dan terus terjadi.
Bahkan konsep yang paling bisa menjelaskan realitas politik dunia setelah Perang Dingin berakhir pada 1989 yang mengakhiri pertarungan ideologi sejak akhir Perang Dunia Kedua.
Yang terjadi kemudian adalah apa yang disebut dengan teorisi hubungan internasional terkenal, Samuel P. Huntington, sebagai "benturan peradaban" atau clash of civilization.
Namun belakangan bukan lagi budaya yang berbenturan, melainkan persaingan pada tingkat sangat dangkal, menyangkut kepentingan nasional atau bahkan status quo kekuasaan.
Pembukaan hubungan diplomatik antara empat negara Arab dengan Israel, mendekatnya Taliban dan China, dan orientasi Indo-Pasifik pemerintahan Joe Biden adalah contoh-contoh dorongan besar realpolitik dalam tata hubungan internasional dewasa ini.
Belum lagi nasionalisme vaksin COVID-19 yang semakin memperlihatkan egoisme negara-negara ketika justru para pemimpinnya aktif menyerukan kolaborasi.
Semua fenomena itu menjelaskan bahwa pertimbangan ideologis termasuk agama dan moral, pupus ketika sudah menyangkut kepentingan nasional. Dalam konteks ini tak ada yang bisa saling mendekatkan negara-negara, sekuat kalkulasi kepentingan nasional.
Baca juga: Prospek negara Palestina saat politisi ultrakanan Israel berkuasa
Baca juga: Menyelamatkan Afghanistan dari krisis kemanusiaan
Selanjutnya: Internasionalisme tak pernah berhasil
Pragmatisme
Internasionalisme pun menjadi tidak laku, bahkan cenderung retorika semata. Sejarah sendiri menunjukkan internasionalisme tak pernah berhasil. Tapi nasionalisme yang terlalu berpusat kepada kepentingan sendiri sebuah negara seperti diambil Donald Trump juga tak laku karena mengecualikan negosiasi yang masih menjadi unsur penting dalam memajukan kepentingan nasional negara mana pun.
Sampai 2014 ketika pasukan koalisi pimpinan AS mulai menarik diri dari Afghanistan, China aktif mempromosikan rekonsiliasi di Afghanistan secara tidak langsung melalui Pakistan. Tetapi secara bertahap pendekatan itu berubah ketika China makin intensif berbicara melalui saluran-saluran bilateral dan multilateral seperti Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO).
Taliban menyambut baik hubungan bilateral dengan China dengan maksud bergabung dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan, menjadi wujud pragmatisme Taliban untuk menjauhkan jihadis global dari wilayah Afghanistan dan memanfaatkan China sebagai sumber finansial utama negeri itu ketika lembaga-lembaga keuangan internasional dan Barat membekukan asset-asset Afghanistan di luar negeri dan akses pinjaman internasional bagi negeri ini.
Bagi China hubungan baik dengan Taliban dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk memastikan Taliban tak memberi tempat kepada jihadis global yang membidik Xinjiang di China yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Tentunya juga ada motif ekonomi di balik itu semua, khususnya dalam kaitannya dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan.
Dari Liga Arab, negara-negara seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab yang merupakan anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), serta Sudan dan Maroko, membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel pada 2020.
Israel dan GCC sama-sama terancam oleh Iran, selain mendapatkan dorongan semangat dari sikap anti-Iran pemerintahan Presiden Donald Trump waktu itu.
Langkah terobosan ini juga wujud dari bentuk kekecewaan negara-negara Teluk terhadap pemerintahan AS sebelum Trump, yakni Barack Obama, karena cenderung merangkul Iran dan mendukung penggulingan pemimpin-pemimpin otokratis di Mesir dan Tunisia pada awal revolusi Arab Spring.
Negara-negara Arab itu juga berusaha mendapatkan perlindungan Israel dari kemungkinan revolusi ala Arab Spring di kemudian masa.
Bagi Israel sendiri, hubungan baik dengan GCC menjadi pintu untuk menutup sumber pendanaan utama Palestina sehingga Palestina bisa ditekan untuk memberikan konsesi-konsesi lebih besar kepada Israel.
Tapi kini Trump tak lagi penguasa Gedung Putih. Sebaliknya Joe Biden yang seperti pendahulunya Barack Obama berasal dari Partai Demokrat, berusaha mengoreksi kebijakan-kebijakan Trump mengenai Palestina dan Israel, bahkan dalam sikap AS terhadap pembunuhan wartawan Arab Saudi Jamal Kashoggi yang disebut-sebut melibatkan Pangeran Mahkota Muhamed bin Salman.
Arab juga melihat hengkangnya AS dari panggung politik Timur Tengah yang ditandai dengan mundurnya mereka dari Irak, yang disusul Afghanistan, membuat Timur Tengah menjadi tak punya payung keamanan sekalipun AS masih mengoperasikan pangkalan militer di Kuwait.
Arab kini merasa kepentingan AS tidak lagi berada di Timur Tengah sehingga ketika konflik terjadi mereka tak lagi bisa mengandalkan intervensi AS.
Saudi bereksperimen membuat koalisi yang mengecualikan AS ketika negara ini dan negara-negara GCC terlibat perang panjang dengan milisi Shiah di negara yang berbatasan langsung dengan wilayah selatan Saudi itu. Dan eksperimen ini tak berhasil karena kelompok syiah Yaman dukungan Iran tak pernah bisa digulingkan oleh koalisi pimpinan Saudi.
Baca juga: Babak baru Beijing-Taliban
Baca juga: Pemerintah pertimbangkan aktivasi kembali KBRI di Kabul
Selanjutnya: Perubahan hubungan internasional
Kepentingan nasional
Kini, negara-negara Arab saling mendekat. Qatar tak lagi bermusuhan dengan Arab Saudi dan negara-negara GCC lainnya. Mereka juga berusaha membuat perimbangan lewat berbicara dengan Iran walaupun tidak melalui saluran terbuka.
Perubahan juga terjadi dalam konteks hubungan AS-Eropa ketika AS, Inggris dan Australia membentuk aliansi strategis baru bernama AUKUS yang merupakan kesepakatan tripartit menyangkut keamanan, teknologi dan berbagi intelijen di antara ketiga negara.
Misi pertama aliansi ini adalah membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir untuk angkatan laut Australia sebagai langkah penting dalam menghadapi semakin agresifnya China di Indo-Pasifik.
Tapi kesepakatan ini dianggap kudeta politik terhadap hubungan AS dan Prancis yang sudah berharap Biden bisa membalikkan orientasi politik luar negeri AS menjadi condong kembali ke Uni Eropa.
Prancis bertambah sewot karena aliansi baru itu menyabotase kesepakatan pertahanan senilai 70 miliar dolar AS antara Prancis dan Australia guna membuat armada kapal selam bertenaga non-nuklir Australia yang kini sudah dibatalkan.
Prancis dan Uni Eropa membalas AS dengan menyatakan tak tertarik kepada aliansi menghadapi China. Eropa tetap menolak ikut bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan dunia. Mereka memilih peluang ekonomi dan perdagangan dengan China ketimbang membuka tirai konflik.
Realpolitik juga menjadi warna utama di balik politik vaksin COVID-19.
Sekalipun sudah lama diprediksi para pakar jauh sebelum vaksin COVID-19 ada, nasionalisme vaksin benar adanya, justru ketika pandemi mengharuskan dunia berkolaborasi, khususnya dalam upaya menyalurkan secara merata vaksin ke seluruh dunia.
Namun yang terjadi negara-negara malah berlomba memvaksinasi dirinya atas pertimbangan realistis sendiri-sendiri yang jauh dari aspek moral, karena melulu didasarkan kepada pertimbangan kepentingan nasional.
Bahkan G20 pun sendiri tetap berkubang dalam retorika menyangkut distribusi vaksin karena memang tak ada satu pun yang mau mengorbankan kepentingan nasionalnya yang di beberapa negara diasosiasikan dengan kepentingan rezim.
Semua ini kian menegaskan bahwa yang mendasari negara-negara bertindak bersama bukanlah pertimbangan moral dan apalagi ideologis.
Kepentingan nasional dan irisan kepentingan nasional di antara merekalah yang memaksa negara-negara beraliansi.
Dalam kata lain, "tak ada musuh dan sekutu yang abadi. Hanya kepentingan nasional yang abadi."
Baca juga: Raja Saudi khawatir tentang program nuklir Iran
Baca juga: Tantangan panglima TNI juga perang siber dan keamanan-geopolitik
Baca juga: AUKUS "point of no return" geopolitik Indo-Pasifik
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Dadan Ramdani
COPYRIGHT © ANTARA 2021