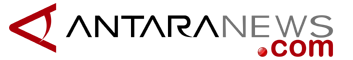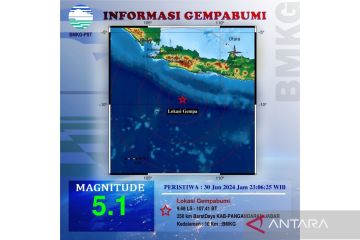Dapat diartikan tema tersebut dalam bahasa Indonesia adalah peringatan dini dan tindakan dini, serta menyoroti pentingnya informasi hidrometeorologi dan iklim untuk pengurangan risiko bencana. Sehingga ini menjadi agenda penting yang harus dijadikan pedoman bagi badan-badan meteorologi sedunia.
WMO sendiri telah merilis informasi suhu rata-rata global pada laporan terakhirnya di awal Desember 2020, menempatkan tahun 2016 sebagai tahun terpanas di peringkat pertama.
Menyusul di tahun 2020, yang yang sedang dalam perjalanannya, tercatat sebagai salah satu dari tiga tahun terpanas yang dirasakan penduduk dunia.
Adapun dalam catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tahun 2016 merupakan tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.8 °C sepanjang periode pengamatan 1981 hingga 2020.
Sementara tahun 2020 sendiri menempati urutan kedua tahun terpanas dengan nilai anomali sebesar 0.7 °C, dengan tahun 2019 berada di peringkat ketiga dengan nilai anomali sebesar 0.6 °C.
Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, kencangnya laju perubahan iklim tersebut menyebabkan Indonesia dihantam oleh masalah yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem.
Tidak hanya intensitasnya yang bertambah, namun menurut Dwikorita, durasinya juga bertambah, mulai dari hujan lebat disertai kilat dan petir, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga hujan es.
Dia mengatakan ketika situasi tersebut bertemu dengan kerentanan lingkungan, maka fenomena cuaca ekstrem tersebut tidak jarang merembet menjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor.
Dwikorita menyoroti kenaikan suhu di Indonesia berdampak pada mencairnya salju abadi di Puncak Jaya, Papua.
Bila awalnya luasan salju abadi sekitar 200 km persegi, maka kini hanya menyisakan 2 km persegi atau tinggal 1 persen saja. Salju dan es abadi di Puncak Jaya, Papua memiliki keunikan, mengingat wilayah Indonesia beriklim tropis.
Fenomena lainnya, munculnya siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 lalu. Bencana tersebut memakan puluhan korban jiwa.
Siklon tropis bisa dikatakan sangat jarang terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Namun selama 10 tahun terakhir, kejadian siklon tropis semakin sering terjadi dan berdampak tidak langsung pada cuaca Indonesia.
Jika menilik dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2022 dari awal Januari hingga Selasa (22/3), tercatat 1.034 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia.
Kejadian alam didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti kejadian banjir (424), cuaca ekstrem (358), tanah longsor (195) dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla (44).
Dampak bencana alam tersebut diantaranya puluhan korban jiwa, dan jutaan penduduk menderita dan mengungsi, disertai kerusakan infrastruktur sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Baca juga: BNPB-BMKG terapkan program IDRIP ke 25 provinsi risiko tinggi tsunami
Baca juga: Dirjen IKP : GPDRR perkuat mitigasi dan penanggulangan bencana global
Peningkatan kapasitas
Maka, ini menjadi momentum bagi BMKG untuk meningkatkan kapasitas peringatan dini dan tindakan dini terhadap fenomena cuaca dan iklim.
Menghadapi berbagai dampak bencana, berbagai upaya dilakukan termasuk mempercanggih teknologi guna melihat kondisi kebencanaan Indonesia secara garis besar.
Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG Muhamad Sadly pada kuliah umum dalam rangka Hari Meteorologi Dunia Ke-72 menyebutkan, saat ini Indonesia membutuhkan sembilan satelit penginderaan jauh dengan orbitan tanpa jeda, untuk memantau kondisi kebencanaan secara keseluruhan di wilayah yang sangat luas.
Dia mengatakan wilayah Indonesia punya ancaman bencana yang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani secara normatif, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang saat ini semakin ekstrem maka dibutuhkan teknologi.
Menurut dia, jika hanya satu satelit maka ada jeda 100 menit saat mengorbit sehingga tidak bisa dilakukan untuk pemantauan bencana.
Tanpa satelit, tambah Sadly, maka akan sulit melakukan pemantauan karena butuh waktu lama sebab wilayah Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke.
Saat bencana terjadi baik gempa, tsunami atau bencana hidrometeorologi lainnya, menurut Sadly, sistem komunikasi akan kolaps. "Kita tidak bisa gunakan komunikasi berbasis HP, apalagi terjadi gempa besar seperti di Palu pada 2018. Lalu bagaimana orang bisa menyelamatkan diri kalau tidak ada sistem komunikasi yang andal," ujar .
Dalam kesempatan yang sama, Prof Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, ahli satelit gelombang mikro dari Universitas Chiba, Jepang memberi solusi dengan merekomendasikan full polarimetric spaceborne Syntethic Aperture Radar (SAR), metode analisis citra radar dengan mengeksploitasi polarisasi citra dengan radar apertur sintetis (SAR) untuk membuat gambar dua dimensi atau rekonstruksi objek tiga dimensi, seperti lanskap.
Menurut Josaphat, Indonesia harus memiliki sensor karena letak wilayah di ekuator dan pertumbuhan awan yang cepat berdampak bencana hidrometeorologi dapat terjadi secara tiba-tiba.
Dia juga menyarankan agar Indonesia membuat satelit sendiri sesuai kebutuhan, bahkan jika perlu teknologi yang dibuat melampaui negara lain. "Dengan satelit, data yang didapat lebih akurat dan cepat sehingga bencana hidrometeorologi seperti hujan, angin kencang, longsor dan lainnya dapat diprediksi," katanya.
Bahkan menurut dia, anggaran yang diperlukan untuk membuat satelit tidak terlalu besar, sekitar Rp150 miliar untuk satu satelit yang pernah ia buat.
Hal ini dengan cara mengkombinasikan satelit meteorological geostasionary untuk meteorologi yang khas Indonesia, yaitu jumlah gelombang dan aplikasinya, dan pembangunan satelit meteorologi menggunakan SDM dan material dalam negeri Indonesia.
Baca juga: KKP diminta perbanyak terapkan riset mitigasi bencana kelautan
Peningkatan kapasitas
Maka, ini menjadi momentum bagi BMKG untuk meningkatkan kapasitas peringatan dini dan tindakan dini terhadap fenomena cuaca dan iklim.
Menghadapi berbagai dampak bencana, berbagai upaya dilakukan termasuk mempercanggih teknologi guna melihat kondisi kebencanaan Indonesia secara garis besar.
Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG Muhamad Sadly pada kuliah umum dalam rangka Hari Meteorologi Dunia Ke-72 menyebutkan, saat ini Indonesia membutuhkan sembilan satelit penginderaan jauh dengan orbitan tanpa jeda, untuk memantau kondisi kebencanaan secara keseluruhan di wilayah yang sangat luas.
Dia mengatakan wilayah Indonesia punya ancaman bencana yang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani secara normatif, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang saat ini semakin ekstrem maka dibutuhkan teknologi.
Menurut dia, jika hanya satu satelit maka ada jeda 100 menit saat mengorbit sehingga tidak bisa dilakukan untuk pemantauan bencana.
Tanpa satelit, tambah Sadly, maka akan sulit melakukan pemantauan karena butuh waktu lama sebab wilayah Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke.
Saat bencana terjadi baik gempa, tsunami atau bencana hidrometeorologi lainnya, menurut Sadly, sistem komunikasi akan kolaps. "Kita tidak bisa gunakan komunikasi berbasis HP, apalagi terjadi gempa besar seperti di Palu pada 2018. Lalu bagaimana orang bisa menyelamatkan diri kalau tidak ada sistem komunikasi yang andal," ujar .
Dalam kesempatan yang sama, Prof Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, ahli satelit gelombang mikro dari Universitas Chiba, Jepang memberi solusi dengan merekomendasikan full polarimetric spaceborne Syntethic Aperture Radar (SAR), metode analisis citra radar dengan mengeksploitasi polarisasi citra dengan radar apertur sintetis (SAR) untuk membuat gambar dua dimensi atau rekonstruksi objek tiga dimensi, seperti lanskap.
Menurut Josaphat, Indonesia harus memiliki sensor karena letak wilayah di ekuator dan pertumbuhan awan yang cepat berdampak bencana hidrometeorologi dapat terjadi secara tiba-tiba.
Dia juga menyarankan agar Indonesia membuat satelit sendiri sesuai kebutuhan, bahkan jika perlu teknologi yang dibuat melampaui negara lain. "Dengan satelit, data yang didapat lebih akurat dan cepat sehingga bencana hidrometeorologi seperti hujan, angin kencang, longsor dan lainnya dapat diprediksi," katanya.
Bahkan menurut dia, anggaran yang diperlukan untuk membuat satelit tidak terlalu besar, sekitar Rp150 miliar untuk satu satelit yang pernah ia buat.
Hal ini dengan cara mengkombinasikan satelit meteorological geostasionary untuk meteorologi yang khas Indonesia, yaitu jumlah gelombang dan aplikasinya, dan pembangunan satelit meteorologi menggunakan SDM dan material dalam negeri Indonesia.
Baca juga: KKP diminta perbanyak terapkan riset mitigasi bencana kelautan
Baca juga: Akademisi: Masyarakat harus dukung program memperkuat mitigasi bencana
Mitigasi
Selain memiliki peran kunci sebagai pusat informasi dan penyebarluasan peringatan dini dan mitigasi bencana, peranan BMKG tersebut dalam sistem peringatan dini tak hanya berhenti sebagai sebuah informasi, melainkan dalam sistem mitigasi bencana.
Dalam mitigasi bencana, diperlukan kesepahaman yang sama antara pemerintah dan semua elemen masyarakat tentang dampak serius perubahan iklim.
Diperlukan aksi mitigasi yang komprehensif dari hulu hingga hilir dengan pelibatan aktif masyarakat dan berbagai pihak termasuk pihak swasta, para akademisi/ilmuwan, filantropi, media, dan lain sebagainya.
Selain itu, gotong royong dalam melakukan aksi mitigasi. Mulai dari pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, gelombang, listrik, serta penghematan listrik, air, pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon atau reboisasi secara lebih masif, restorasi mangrove, dan lain sebagainya.
Dwikorita mengatakan cara-cara yang dianggap sepele tersebut akan berdampak sangat luar biasa terhadap keberlangsungan bumi dan umat manusia.
Ia mengingatkan, percuma saja pemerintah melakukan aksi di hulu, kalau tapi di hilir masyarakat tetap melakukan aksi perusakan lingkungan, atau sebaliknya.
Seminar, konferensi, edukasi kepada masyarakat, pameran lomba-lomba terkait dengan meteorologi dan kegiatan lainnya terus diadakan untuk meningkatkan kesadaran dampak bencana alam.
BMKG terus menggelar berbagai kegiatan untuk literasi masyarakat terkait pemanfaatan data meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan peringatan dini serta aksi dini.
Diantaranya dengan Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) dan Sekolah Lapang Cuaca bagi Nelayan (SLCN).
Tentu saja, hal tersebut untuk menekankan penguatan pengelolaan kegiatan peringatan dini dan aksi dini, dengan cara yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Semua hal itu saling berkaitan erat antara peringatan dini, aksi dini dan usaha meminimalkan dampak akibat bencana hidrometeorologi.
Baca juga: Strategi pentahelix dibutuhkan untuk bangun budaya mitigasi bencana
Mitigasi
Selain memiliki peran kunci sebagai pusat informasi dan penyebarluasan peringatan dini dan mitigasi bencana, peranan BMKG tersebut dalam sistem peringatan dini tak hanya berhenti sebagai sebuah informasi, melainkan dalam sistem mitigasi bencana.
Dalam mitigasi bencana, diperlukan kesepahaman yang sama antara pemerintah dan semua elemen masyarakat tentang dampak serius perubahan iklim.
Diperlukan aksi mitigasi yang komprehensif dari hulu hingga hilir dengan pelibatan aktif masyarakat dan berbagai pihak termasuk pihak swasta, para akademisi/ilmuwan, filantropi, media, dan lain sebagainya.
Selain itu, gotong royong dalam melakukan aksi mitigasi. Mulai dari pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, gelombang, listrik, serta penghematan listrik, air, pengelolaan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon atau reboisasi secara lebih masif, restorasi mangrove, dan lain sebagainya.
Dwikorita mengatakan cara-cara yang dianggap sepele tersebut akan berdampak sangat luar biasa terhadap keberlangsungan bumi dan umat manusia.
Ia mengingatkan, percuma saja pemerintah melakukan aksi di hulu, kalau tapi di hilir masyarakat tetap melakukan aksi perusakan lingkungan, atau sebaliknya.
Seminar, konferensi, edukasi kepada masyarakat, pameran lomba-lomba terkait dengan meteorologi dan kegiatan lainnya terus diadakan untuk meningkatkan kesadaran dampak bencana alam.
BMKG terus menggelar berbagai kegiatan untuk literasi masyarakat terkait pemanfaatan data meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan peringatan dini serta aksi dini.
Diantaranya dengan Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) dan Sekolah Lapang Cuaca bagi Nelayan (SLCN).
Tentu saja, hal tersebut untuk menekankan penguatan pengelolaan kegiatan peringatan dini dan aksi dini, dengan cara yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Semua hal itu saling berkaitan erat antara peringatan dini, aksi dini dan usaha meminimalkan dampak akibat bencana hidrometeorologi.
Baca juga: Strategi pentahelix dibutuhkan untuk bangun budaya mitigasi bencana
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2022