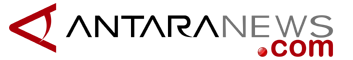"Arab Spring" menggulingkan presiden Tunisia Zine el Abidine Ben Ali dan Hosni Mubarak, presiden Mesir, dan kini terus mengguncang pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad setelah melicinkan jalan bagi tersingkirnya presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.
Gelombang protes dimulai pada Desember 2010, saat seorang pedagang sayur Tunisia membakar dirinya, kemudian gelombang protes itu semakin membesar dan mencapai puncaknya dengan tewasnya Muammar Gaddafi. Kejadian-kejadian tersebut mengurai harapan banyak orang Arab mengenai kebebasan menyampaikan pendapat serta hak dasar lain.
"Kami merampas senjata dari Gaddafi dan menggunakannya terhadap dirinya untuk meraih kebebasan kami. Sekarang kami ingin demokrasi," kata Ali Deeb, teknisi listrik yang berusia 55 tahun dari Tripoli.
"Kami sudah mencium aroma demokrasi dan tak seorang pun perlu takut pada senjata kami. Kami tahu cara mengendalikannya. Tapi kami takkan mentoleransi adanya diktator atau partai politik tunggal lagi. Semua hari itu sudah sirna bersama Gaddafi," kata lelaki yang berusia di atas setengah baya tersebut.
Tak ada perayaan Tahun Baru di Libya, yang kebanyakan warganya berfaham konservatif dan mereka memilih tinggal di dalam rumah di tengah cuaca sangat dingin dan padamnya listrik.
Namun 2012 menjadi tahun "bebas" pertama buat mereka setelah berakhirnya beberapa dasawarsa pemerintah Gaddafi dengan kematiannya pada 20 Oktober.
Puluhan ribu pria Libya mengambil senjata dan menggempur pendukung kuat Gaddafi. Aksi perlawanan brutal mereka menyelimuti jatuhnya presiden yang puluhan tahun memerintah di negara tetangganya, Hosni Mubarak --yang sekarang diadili dengan tuntutan pembunuhan ratusan pemrotes yang bangkit menentang dia di Bundaran At-Tahrir di ibu kota negeri itu, Kairo.
Aksi perlawanan di Mesir masih belum selesai, kata warga Kairo sebagaimana dipantau Antaranews di Jakarta, Selasa (2/1). Beberapa warga ibu kota Mesir tersebut menyampaikan keraguan mengenai pemerintah negeri tersebut oleh junta militer yang mengambil alih wewenang ketika Mubarak meletakkan jabatan.
"Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan guna mencapai sistem demokrasi yang kami upayakan," kata Omar Salem (32), konsultan teknologi informasi di Kairo.
"Pemilihan anggota parlemen menjadi titik awal tapi karena militer masih berkuasa, kami tak tahu ke arah mana negara ini akan pergi," kata Salem.
Warga Mesir ingin membangun lembaga negara yang efisien yang mereka katakan menjadi "masalah terbesar" di bawah Mubarak.
"Saya berharap kami memiliki parlemen yang sesungguhnya, polisi sesungguhnya dan hakim yang jujur sehingga kami bisa mulai membangun negeri ini," kata Amir Said --yang bekerja buat satu perusahaan keamanan swasta.
"Saya tidak khawatir mengenai kubu Islam di parlemen. Mereka datang melalui pemilihan umum sejati. Jika mereka bekerja dengan baik, biarkan mereka tetap di parlemen. Jika mereka tak bekerja dengan baik, rakyat tak lagi takut untuk menyerukan perubahan," katanya.
Pemilihan umum di Tunisia, tempat awal "Arab Spring", mengantar kubu Islam ke tampuk pimpinan.
"Saya optimistis sekarang, tapi saya tak yakin apakah kebebasan saya yang kecil seperti kebebasan buat perempuan akan berhasil dan cara berpakaian akan seperti sekarang dengan partai Islam berkuasa," kata guru filsafat di Tunisia, Zakia Ammar.
Namun ia mengakui mahasiswanya tidak lagi "takut untuk membicarakan masalah seperti agama dan politik di ruang kelas".
"Mereka mendesak garis merah dan itu menjanjikan banyak buat kreativitas mereka pada masa depan," katanya.
Tantangan
Ada beberapa tantangan bagi demokrasi di Libya, Mesir, Yaman dan di Suriah, tempat tantangan sembilan-bulan terhadap kekuasaan Presiden Bashar al-Assad berkobar di bawah penindasan. PBB memperkirakan lebih dari 5.000 orang telah tewas.
Insinyur Libya, Deeb, yang merujuk kepada lebih dari 150 miliar dolar AS dana Libya yang dibekukan di luar negeri, mengatakan, "Salah satu dasar utama untuk membangun sistem demokratis yang aktif ialah arus uang ke dalam sistem itu. Kami ingin dana kami dikembalikan."
"Kami akan membuat landasan demokrasi. Kami memerlukan prasarana, kami memerlukan pekerjaan baru dan pendidikan baik buat anak lelaki dan anak perempuan kami. Kami harus membangun Libya baru dan, untuk itu, kami perlu memperoleh kembali uang kami," katanya.
Pandangannya dikumandangkan oleh warga lain Tripoli, ibu kota Libya, Mukhtar, seorang pensiunan pegawai negeri yang hanya menyebutkan nama depannya dan mengatakan, "Kekurangan parah uang kontan telah membuat hidup jadi berat di Libya."
Namun optimisme umum yang ada menjadi jelas di semua negara itu saat Tahun Baru menyambangi.
"Tahun 2011 adalah tahun yang luar biasa, saat kaum muda mengakhiri kebungkaman yang dilakukan orang tua mereka. Mereka membuktikan rakyat tak bisa dikalahkan," kata pegiat dan penulis Yaman Abd ash-Shafi.
"Saya berharap 2012 akan mempertahankan momentum yang sama dan memberi manfaat bagi `Arab Spring`," ia menambahkan.
(C003/A011)
Editor: Ella Syafputri
COPYRIGHT © ANTARA 2012