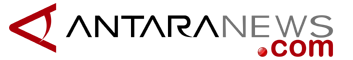Di dunia, posisi Indonesia sebagai negara eksportir CPO cukup disegani; wajar jika komoditas ekspor ini masih menjadi salah satu komoditas unggulan nonmigas nasional.
Singkat kata, prospek industri dari tanaman kelapa sawit (Elaeis jacque sp) masih menjanjikan di Indonesia. Benarkah begitu? Simak pernyataan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), M Fadhil Hasan.
"Setiap tahun keuntungan komparatif CPO terus tumbuh," ujarnya, pada lokakarya tentang membangun industri kelapa sawit berkelanjutan, di Bogor, beberapa waktu lalu.
Laiknya pebisnis, dia bicara memakai data. Gapki mendata, sejak 2000-2008 tingkat daya saing CPO terus meningkat angka, dari 24,1 menjadi 41,05. Timah dari sektor pertambangan di posisi kedua, yang juga meningkat dari 13,45 ke 37,55 yang berarti peningkatan lebih dari dua kali lipat.
Walau daya saing komparatif CPO tinggi di pasar internasional, tidak otomatis membuat komoditas nabati itu melenggang bebas mendominasi pasar minyak nabati dunia. Salah satunya persaingan internasional dengan minyak nabati lain, di antaranya minyak kedelai dan minyak bunga matahari.
Laiknya pebisnis, dia bicara memakai data. Gapki mendata, sejak 2000-2008 tingkat daya saing CPO terus meningkat angka, dari 24,1 menjadi 41,05. Timah dari sektor pertambangan di posisi kedua, yang juga meningkat dari 13,45 ke 37,55 yang berarti peningkatan lebih dari dua kali lipat.
Walau daya saing komparatif CPO tinggi di pasar internasional, tidak otomatis membuat komoditas nabati itu melenggang bebas mendominasi pasar minyak nabati dunia. Salah satunya persaingan internasional dengan minyak nabati lain, di antaranya minyak kedelai dan minyak bunga matahari.
Di dalam negeri, ada lagi cerita lain yang harus dientaskan, bernama peraturan dan kebijakan terkait minyak kelapa sawit yang diterapkan pemerintah.
"Tantangan yang tidak kalah besar justru dari dalam negeri," ujar Hasan.
Tentang ekspor minyak kelapa sawit, pemerintah menetapkan kebijakan pajak ekspor tersendiri, yang lebih akrab dikenal sebagai bea keluar.
"Tantangan yang tidak kalah besar justru dari dalam negeri," ujar Hasan.
Tentang ekspor minyak kelapa sawit, pemerintah menetapkan kebijakan pajak ekspor tersendiri, yang lebih akrab dikenal sebagai bea keluar.
Gapki menilai kebijakan tersebut kontraproduktif terhadap upaya peningkatan ekspor komoditas itu. Selain dinilai tidak konsisten, dia menyatakan, "Secara substantif kami menolak bea keluar, karena tujuan yang satu dengan yang lain bertolak belakang."
Dari sisi pemerintah, ada alasan menetapkan bea keluar itu, sebutlah mulai dari stabilisasi harga minyak goreng, rehabilitasi lingkungan, instrumen hilirisasi untuk pengembangan produk turunan CPO di dalam negeri, dan instrumen penerimaan negara.
Dia membandingkan instrumen kebijakan itu dengan yang terjadi di Malaysia, pesaing terdekat Indonesia. "Dengan BK diberlakukan, volume ekspor CPO lebih rendah bila dibandingkan dengan tanpa BK," ujarnya.
Sudahlah di dalam negeri dikenakan bea keluar, di negara penerima alias tujuan ekspor, CPO juga menjadi obyek pajak impor dan turunannya; untuk melindungi produk-produk minyak nabati mereka. "Selain itu ada juga hambatan teknis di beberapa negara tujuan ekspor," ujar dia.
Ia mencontohkan beberapa negara pengimpor yang dimotori negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang menerapkan standar teknis terkait aspek lingkungan, di antaranya emisi dan penyerapan karbon, serta pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
"Penerapan sertifikasi menjadi bagian penting dari pemenuhan standar teknis perdagangan itu," katanya, sambil merujuk pada standar Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang berlaku di pasar internasional, terutama Eropa dan Amerika Serikat.
Tantangan lain, beberapa negara juga menerapkan label untuk produk yang menggunakan kelapa sawit, di antaranya pada makanan; terkait aspek kesehatan. "Perancis dan Australia merupakan dua negara yang menerapkan pelabelan untuk produk kelapa sawit," ujar dia.
Ditengarai produk berbasis kelapa sawit tidak sehat dibandingkan minyak nabati lain. Gapki menduga, wacana itu bagian dari perang dagang dan persaingan untuk meredam laju minyak sawit, yang produksinya lebih efisien dibanding minyak nabati lain.
Ketua Bidang Budidaya dan Industri Dewan Minyak Sawit Indonesia, Daud Darsono, mengatakan, pada 2012 minyak sawit telah mendominasi pasar minyak nabati dunia. Data Oil World, total konsumsi minyak nabati dunia mencapai 150 juta ton dan sekitar 34 persen dipasok minyak sawit.
Pada tahun sama, pangsa pasar minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai hanya 28 persen, minyak rapeseed sebesar 16 persen, dan bunga matahari sebesar 10 persen saja.
Apapun tantangannya, industri komoditas yang tanaman aslinya berasa dari Pulau Madagaskar, Afrika Timur itu terus tumbuh di Indonesia. Indikator yang diungkap Gakpi adalah kepemilikan kebun kelapa sawit oleh rakyat.
Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Gapki, Tungkot Sipayung, mengatakan, sejak 1980 sampai sekarang, kepemilikan lahan usaha kelapa sawit oleh mayarakat berkembang pesat.
Kepala Bidang Hukum dan Advokasi Gapki, Tungkot Sipayung, mengatakan, sejak 1980 sampai sekarang, kepemilikan lahan usaha kelapa sawit oleh mayarakat berkembang pesat.
"Sekarang ini, rakyat telah menguasai 42 persen perkebunan kelapa sawit seluas 3,3 juta hektare. " ujarnya. Sekitar 80 persen perkebunan rakyat itu dibiayai mereka sendiri, tanpa bantuan modal pemerintah.
Padahal, lanjut dia, saat awal pengembangan kelapa sawit pada 1979, BUMN perkebunan mendominasi pengelolaan lahan komoditas itu, dengan komposisi 68 persen berbanding 32 persen oleh swasta.
Kini, kata dia, BUMN hanya menguasai delapan persen perkebunan kelapa sawit. "Menurut saya itulah bentuk keberhasilan BUMN dalam pembangunan. Tugas BUMN membantu rakyat agar tidak jadi beban negara," ujar Sipayung, yang juga pejabat di BUMN perkebunan.
Padahal, lanjut dia, saat awal pengembangan kelapa sawit pada 1979, BUMN perkebunan mendominasi pengelolaan lahan komoditas itu, dengan komposisi 68 persen berbanding 32 persen oleh swasta.
Kini, kata dia, BUMN hanya menguasai delapan persen perkebunan kelapa sawit. "Menurut saya itulah bentuk keberhasilan BUMN dalam pembangunan. Tugas BUMN membantu rakyat agar tidak jadi beban negara," ujar Sipayung, yang juga pejabat di BUMN perkebunan.
(R016//Z002)
Oleh Risbiani Fardaniah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2013