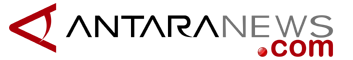“Memperlakukan secara sama semua bentuk penyiaran dengan argumentasi bahwa adanya ketidakadilan ini sulit diterima, ya, karena dalam kenyataannya, dan juga kalau kita bandingkan dengan praktik-praktik di beberapa negara, memang ada perbedaan antara regulasi untuk penyiaran internet dengan penyiaran terestrial,” kata Eriyanto dalam diskusi yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi perluasan cakupan pengawasan penyiaran dalam RUU tersebut, yakni dari penyiaran terestrial saja menjadi meliputi penyiaran dalam internet.
Menurut dia, penyiaran berbasis frekuensi menggunakan frekuensi yang sifatnya terbatas, dan penonton tidak memiliki kebebasan untuk mengendalikan tontonannya.
“Dan argumentasi ini yang kemudian mendasari kenapa di banyak literatur dan juga di praktik-praktik yang terbaik di luar negeri, penyiaran yang berbasis frekuensi itu selalu regulasinya itu sifatnya ketat. Kenapa? Karena regulator harus menjalankan bahwa penyiaran itu bisa diterima oleh semua usia dan seterusnya,” jelasnya.
Sementara itu, kata dia, penyiaran yang berbasis internet memiliki perbedaan dengan penyiaran terestrial karena penonton mempunyai kendali yang tidak terbatas. Kemudian, lanjut dia, penyedia penyiaran tidak membutuhkan lisensi seperti penyiaran yang berbasis frekuensi.
“Dari beberapa literatur disebut bahwa regulasi yang sifatnya ketat itu terutama ditujukan untuk penyiaran yang sifatnya terestrial. Kenapa? Karena harus ada lisensi. Jadi, tidak semua orang bisa mendirikan lembaga penyiaran, kemudian ada standar isi siaran yang harus dicermati,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “kemudian internet yang OTT (over-the-top) itu regulasinya lebih ringan. Kenapa? Karena argumentasinya itu adalah dalam OTT khalayak itu bisa memilih konten yang dia sukai.”
Ia juga mengatakan siaran internet yang berbentuk user-generated content (UGC) atau konten dari pengguna juga tidak perlu diatur dengan regulasi yang ketat.
“Karena di dalam user-generated content itu khalayak di sini bukan hanya punya pilihan, ya, tetapi khalayak itu pada dasarnya ya produsen itu sendiri. Itu kan setiap orang bisa ya membuat live (siaran langsung) Instagram, live TikTok, dan seterusnya, karena itu biasanya regulasinya lebih ringan,” jelasnya.
Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa merupakan kewajaran untuk merevisi UU Penyiaran, terutama untuk merespons perkembangan teknologi. Akan tetapi, ia menyebut masih banyak terjadi kesalahan, seperti menggunakan logika penyiaran.
“Jadi, disebut secara jelas dalam naskah akademik itu adalah adanya ketidakadilan. Jadi, kata kuncinya adalah ketidakadilan bagaimana lembaga penyiaran itu wajib mengurus lisensi, mengurus izin, sementara platform digital tidak,” katanya.
Ia melanjutkan, “kemudian disebut juga ketidakadilan yang lainnya adalah sementara lembaga penyiaran terestrial mendapatkan pengawasan, sementara platform digital tidak mendapatkan pengawasan, dan itu yang kemudian menjadi semangat kenapa cakupannya itu diperluas.”
Baca juga: Anggota DPR: RUU Penyiaran bertujuan untuk harmonisasi UU Ciptaker
Baca juga: Wapres tekankan investigasi dalam RUU Penyiaran adalah hak publik
Baca juga: Jurnalis Bali nilai RUU Penyiaran berpotensi ancam kerja jurnalistik
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024