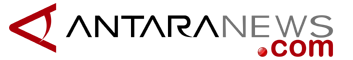The Economist Intelligent Unit (EIU) juga menempatkan Indonesia berada di kategori “flawed democracy” atau “demokrasi cacat”, dan menempati urutan ke-56 di dunia dengan skor total 6,53 pada tahun 2023.
Pasca-amendemen ke-4 tahun 2002, politik demokrasi Indonesia cenderung executive heavy. Hal ini karena sistem demokrasi parlementer, yang dipraktikkan pada masa sebelum amendemen UUD, diubah menjadi sistem presidensial (Pasal 4 UUD). Hal ini dipertegas dengan mekanisme pemilihan presiden secara langsung melalui pemilihan umum.
Dengan demikian, bandul kekuasaan di republik ini hampir benar-benar-- jika tidak disebut mutlak--dikuasai oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Peristiwa perubahan sistem politik ini kemudian sangat disesali oleh Prof. Amien Rais, eks Ketua MPR yang menjadi pelaku sejarah amendemen UUD.
Perubahan struktur dan sistem parlemen dari sebelumnya unikameral menjadi bikameral tentu memiliki tujuan yang baik dan tepat dalam konteks Indonesia karena Indonesia memiliki karakter wilayah dan tingkat heterogenitas yang sangat kompleks. Keberadaan kamar kedua dalam lembaga parlemen yang kemudian disebut sebagai DPD RI, yang notabene nonpartisan, sangat penting dalam menyampaikan aspirasi daerah dan memastikan terjadinya mekanisme check and balance.
DPD tidak hanya dibutuhkan sebagai penyeimbang konfigurasi politik legislasi dan anggaran di level nasional, namun juga menjadi tempat berkumpulnya para elite daerah (senator) untuk menggodok kebijakan yang prodaerah. Mengingat adanya trauma sejarah, yang bahkan masih aktif mengancam keutuhan NKRI oleh separatis seperti GAM hingga OPM di daerah terjauh hingga saat ini. Alasan ini cukup dijadikan sebagai gagasan dasar untuk memperkuat lembaga DPD.
Pada prinsipnya, keberadaan DPD atau utusan daerah pada masa lalu merupakan upaya untuk menerobos ketidakpuasan atas keterwakilan politik melalui anggota DPR. Dengan legitimasi politik yang sudah lebih kuat karena dipilih langsung melalui pemilu, UUD, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), serta UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) justru memberikan kewenangan minimal kepada DPD.
Kurangnya kewenangan DPD ini kemudian mendapatkan sorotan dari para pengamat dan ahli hukum tata negara.
Prof. Valina Singka Subekti dalam bukunya "Dinamika Konsolidasi Demokrasi", menyoroti kesenjangan kewenangan antara DPR dan DPD. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia itu, terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaian antara ketentuan dalam konstitusi dengan pengaturan dalam UU MD3.
Pertama, dalam penafsiran kalimat "ikut membahas" RUU bersama DPR yang hanya pada tingkat satu. Kedua, ketidakjelasan atau disharmoni hubungan DPR dan DPD dalam fungsi pengawasan yang mana hasil pengawasan DPD sering kali dianggap tidak akuntabel dan terkesan tidak berguna. Ketiga, ketidakjelasan hubungan DPD dengan DPRD dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah.
Namun sayangnya, UUD hasil amendemen nyatanya masih setengah hati memberikan kewenangan politik kepada DPD, dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif. Dalam Pasal 22D UUD, DPD hanya berwenang mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.
Dalam statusnya sebagai lembaga perwakilan, DPD bahkan hanya diberikan kesempatan untuk membahas RUU terkait dan memberikan pertimbangan kepada DPR dan Pemerintah hingga pembahasan tingkat satu.
DPD tidak diakui oleh konstitusi sebagai lembaga legislatif yang memiliki kuasa dan kewenangan untuk menyusun UU, namun hanya sebagai pengusul dan pertimbangan kepada DPR. Anomali sistem bikameral pada lembaga parlemen ini sangat kontradiktif dengan semangat desentralisasi kekuasaan dan konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi.
Sejatinya, ideal tidaknya kewenangan dan peran DPD dapat menjadi barometer untuk mengukur seberapa optimal agenda konsolidasi demokrasi khususnya dalam konteks desentralisasi kekuasaan dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konstitusional yang taktis dalam memperjuangkan kewenangan yang ideal bagi lembaga DPD. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPD dalam memperjuangkan kewenangan lembaga DPD.
Pertama, memperkuat hubungan dan meningkatkan komunikasi politik dengan mitra parlemen DPR, khususnya dengan para ketua umum partai politik. Harmonisasi hubungan politik kedua lembaga perwakilan sangat penting dalam meningkatkan kualitas produk legislasi (UU), memastikan stabilitas politik, dan mendorong optimalisasi konsolidasi demokrasi.
Paradigma MPR sebagai rumah bersama (joint session) DPR dan DPD perlu dibangun guna menghilangkan ego sektoral dan meniadakan segregasi politik kedua lembaga. Oleh karena itu, perlu dibangun agenda bersama dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPD dan DPR. Dalam konteks legislasi, DPR dan DPD perlu menerapkan mekanisme double check terhadap setiap RUU yang diajukan.
Kedua, mengusulkan penambahan kewenangan MPR dalam fungsinya menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Desain dan strategi pembangunan nasional harus dirancang secara tetap dan terukur dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila oleh MPR untuk dijalankan oleh presiden sebagai pelaksana pemerintahan.
Pimpinan MPR RI mestinya menjadi jabatan istimewa yang diberikan kepada pimpinan partai politik dan satu utusan kelompok DPD.
Ketua umum partai politik yang lolos ambang batas parlemen atau parliament threshold, secara etika harusnya dilarang untuk menjadi pembantu presiden atau menteri kabinet. Ketua umum parpol adalah tokoh bangsa dan negarawan yang berperan sebagai majelis syura bagi DPR dan DPD.
Ketiga, mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR merevisi ketentuan kewenangan dan proses legislasi DPD dalam UU MD3 dan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada kedua Undang-undang tersebut, DPD perlu dilibatkan atau bahkan diberikan kewenangan khusus, atau setidaknya sama dengan DPR dalam penyusunan, perubahan, pembahasan, dan penetapan RUU yang terkait dengan otonomi daerah, sesuai Pasal 22D UUD. Dengan demikian produk UU yang merupakan usulan DPD harus juga diakui sebagai RUU usulan DPD.
Pada akhirnya, MPR diharapkan dapat mengakomodasi usulan memperkuat kewenangan DPD, dengan menambahkan ketentuan "DPD memegang kekuasaan membentuk UU" dalam konstitusi.
Terakhir, adalah meningkatkan kapasitas manajemen dan anggaran lembaga DPD secara internal. DPD harus didesain sebagai lembaga parlemen modern yang aktif dalam pembangunan daerah (lokal) sekaligus mampu berdiplomasi di level global untuk mempromosikan potensi nasional dan lokal.
Dengan demikian eksistensi DPD lebih terasa dampaknya bagi masyarakat dan daerah. Intensitas kunjungan ke daerah pemilihan perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan daerah, terutama bagi senator yang berasal dari daerah otonomi khusus dan daerah 3T, mengingat tingkat kompleksitas persoalan di daerah-daerah tersebut.
*) Sultan B. Najamuddin adalah Wakil Ketua DPD RI
Editor: Achmad Zaenal M
Pewarta: Sultan B. Najamuddin *)
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2024