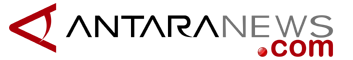Kehidupan di kota besar dikaitkan dengan risiko depresi hampir 40 persen lebih tinggi ketimbang mereka yang tinggal di perdesaan, sehingga orang kota menjadi rentan mengalami gangguan jiwa, mulai tingkat sederhana hingga berat.
Dampak buruk kehidupan perkotaan terhadap kesehatan fisik tidak hanya berdampak pada tingginya angka penyakit degeneratif, namun juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental.
Risiko terkena gangguan mental berupa stres, kecemasan dan depresi, menjadi situasi gangguan jiwa yang paling umum terjadi di dunia, ditandai dengan suasana hati yang buruk dan perasaan tidak berdaya. Kondisi itu, persentasenya 20 persen lebih tinggi pada penduduk kota daripada mereka yang tinggal di luar perkotaan.
Sementara itu, risiko terkena psikosis berupa gangguan kejiwaan berat yang terkait dengan halusinasi, delusi, paranoia, dan pikiran tidak teratur angkanya 77 persen lebih tinggi pada penduduk kota daripada penduduk desa.
Demikian pula, risiko terkena gangguan kecemasan umum, berupa perasaan cemas, khawatir dan perasaan panik mencatat angka 21 persen lebih tinggi pada penduduk kota daripada penduduk desa.
Pada peristiwa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tahun pertama pandemi, prevalensi kecemasan dan depresi global meningkat hingga 25 persen, menurut laporan ilmiah yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Laporan tersebut juga menyoroti siapa yang paling terdampak dan merangkum dampak pandemi terhadap ketersediaan layanan kesehatan mental dan bagaimana hal ini berubah selama pandemi.
Kekhawatiran tentang potensi peningkatan kondisi kesehatan mental telah mendorong 90 persen negara yang disurvei untuk memasukkan dukungan kesehatan mental dan psikososial dalam respons COVID-19, tetapi kesenjangan dan kekhawatiran besar masih tetap ada.
“Informasi yang kami miliki saat ini mengenai dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental dunia hanyalah puncak gunung es. Ini merupakan seruan bagi semua negara untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan mental dan melakukan upaya yang lebih baik dalam mendukung kesehatan mental masyarakatnya," kata Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Salah satu penjelasan utama peningkatan kesehatan mental tersebut adalah stres yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh isolasi sosial akibat pandemi. Hal ini terkait dengan keterbatasan kemampuan orang untuk bekerja, mencari dukungan dari orang yang dicintai, dan terlibat dalam komunitas mereka.
Kesepian, ketakutan akan infeksi, penderitaan dan kematian bagi diri sendiri dan orang yang dicintai, kesedihan setelah berkabung, dan kekhawatiran finansial juga disebut-sebut sebagai pemicu stres yang menyebabkan kecemasan dan depresi. Di kalangan petugas kesehatan, kelelahan telah menjadi pemicu utama pemikiran untuk bunuh diri.
Kondisi gangguan mental pada tingkat sederhana hingga berat nyaris terjadi secara global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang ikut merasakan dampak pada sektor ketenagakerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut data Kemnaker RI tercatat hingga 2,8 juta korban PHK di era pandemi COVID-19, bahkan Kementerian Keuangan menyebutkan PHK mencapai angka hingga 5 juta orang.
Keseimbangan
Kesehatan fisik harus diimbangi dengan kesehatan jiwa yang baik agar hidup menjadi lebih tenang, tenteram dan produktif. Hanya saja, masyarakat kebanyakan umumnya masih enggan untuk menyadari dan peduli terhadap kesehatan jiwanya karena stigma dan atribusi yang diberikan terhadap berbagai perilaku yang dikaitkan dengan kesehatan mental.
Dr. dr. Warih Andan Puspitosari, M.Sc., Sp.Kj. (K), dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY) yang juga praktisi ahli dalam bidang kesehatan jiwa dan mental, mengingatkan jika dibandingkan dengan masalah kesehatan fisik, permasalahan kesehatan jiwa dan mental di Indonesia sangat terlihat jauh kesenjangannya.
Layanan kesehatan jiwa atau masalah mental di Indonesia belum merata. Data menunjukkan 90 persen orang di Indonesia belum mendapatkan penanganan yang tepat untuk masalah mentalnya di enam bulan pertama, sehingga kita perlu meningkatkan layanan kesehatan mental yang merata dan setara di Indonesia.
Penyakit mental belum diperlakukan selayaknya penyakit fisik yang secara normatif dianggap sebagai sesuatu yang biasa untuk diperbincangkan, dikeluhkan, dan diatasi dengan dukungan dari orang di sekitar. Ketika fisik mulai merasakan tidak nyaman, seseorang bisa mengeluhkan badannya terasa pegal, kepala pusing, perut mulas, dan sebagainya tanpa merasa canggung atau malu mengungkapkannya.
Tidak demikian jika seseorang memiliki keluhan terhadap kesehatan mental. Individu yang mengalami perasaan cemas berlebihan atau perasaan sedih terus menerus atau bersikap temperamental, berlama-lama mengurung diri, sulit tidur, perasaan tersebut hanya secara terbuka diungkapkan kepada orang di sekitar yang sudah dipercaya.
Masyarakat kebanyakan, dengan mudah memvonis seseorang yang mengalami perubahan mental tanpa lebih dahulu mencari tahu akar permasalahannya. Apalagi saat ini muncul istilah-istilah di kalangan generasi muda terkait kesehatan mental yang jelas-jelas merugikan individu tertentu.
Media massa dan media sosial memegang peranan besar dalam membentuk persepsi masyarakat tentang penyakit mental. Media sosial kerap mengaburkan batas antara depresi berat dengan stres, kecemasan ringan, kepanikan sekadar sebagai sebuah julukan untuk memberi kesan keren, tetapi justru menyesatkan.
Kerap ditemui di media sosial, istilah-istilah "toxic", "gaslight", "narcissist", dan sebagainya yang digunakan para netizen untuk menjuluki seseorang yang mengacu pada gangguan mental yang disalahartikan hingga tidak tempat penggunaannya. Seperti kata toxic sebagai bahasa gaul di medsos kerap dipakai oleh pengguna dengan konteks untuk membicarakan seseorang dalam hubungan sosial (bisa hubungan percintaan atau hubungan keluarga) yang berlebihan.
Padahal, setiap orang, menurut ahli jiwa pernah mengalami kondisi itu, tapi bukan dalam konteks gangguan jiwa, melainkan sebatas dalam konteks kesehatan jiwa biasa, seperti stres pikiran, bisa terjadi pada setiap orang. Masyarakat awam tidak memiliki kompetensi menyatakan individu itu mengalami gangguan jiwa karena perlu ada tahap diagnosis dan panduan yang dipahami oleh ahli dan profesional.
Kesadaran masyarakat Indonesia terkait kesehatan mental saat ini cukup baik, dibuktikan dengan banyaknya platform digital, organisasi dan LSM yang bergerak di bidang kesehatan mental di kota-kota besar yang mengampanyekan tentang "mental awareness".
Kampanye dan sosialisasi hingga ke akar rumput tentang kesadaran dan kepedulian terhadap penyakit mental perlu digencarkan seiring dengan tingginya stimulan yang memicu timbulnya masalah kesehatan mental, khususnya masyarakat perkotaan yang kental dengan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kemacetan, tekanan ekonomi, polusi, kepadatan permukiman.
Masalah kesehatan jiwa atau mental ini adalah salah satu permasalahan yang serius yang harus menjadi atensi dan kepedulian bersama, apalagi setelah kejadian pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap kesehatan mental masyarakat dan individu, selayaknya menjadi pelajaran berharga untuk menyayangi, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental masing-masing individu.
Pewarta: Zita Meirina
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2024