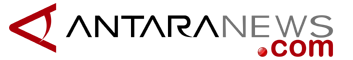Pada fase inilah, muncul masalah terkait dengan otonomi individu. Pada prinsipnya setiap orang berhak menentukan dan menikmati kehidupan pribadi tanpa terstigmatisasi dan terganggu oleh sesuatu apa pun, termasuk oleh kejadian di masa lampau terkait dengan dirinya.
Individu memiliki hak untuk melindungi informasi tentang dirinya di masa lalu sehingga tidak menjadi bahan bagi pihak lain untuk menyerang atau menjatuhkannya. Dalam perbincangan tentang privasi dan internet di benua biru Eropa dewasa ini, dikumandangkan prinsip "the right to silence on past events in life that are no longer occurring."
Persoalannya, teknologi internet berkembang sedemikian rupa sehingga menghasilkan kemampuan untuk merekam dan menyebarluaskan informasi tentang seseorang tanpa disadari oleh orang tersebut. Kemampuan ini dimiliki perusahaan penyedia layanan media sosial, mesin pencari, ecommerce, dan semacamnya.
Penyebarluasan informasi melalui search engine atau media sosial misalnya, bersifat massif atau permanen dan tak terhapuskan dengan menimbulkan dampak terhadap kepentingan pribadi atau partikular berbagai pihak.
Muncul kemudian inisiatif untuk menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan penghapusan informasi teks, video, foto atau akses informasi digital yang tidak relevan lagi atau berpotensi merugikan kepentingan seseorang.
Dalam konteks yang sama, regulasi tentang the right to be forgotten –sebagaimana terlembagakan dalam European Data Protection Directive dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Dengan “hak-untuk-dilupakan” ini, kita dapat menuntut kepada google, facebook, twitter untuk menghapuskan setidaknya dua hal terkait dengan diri kita:
1. Dokumen, data, foto yang pernah kita simpan atau sebarkan melalui platform mereka
2. Data-perilaku-pengguna-internet kita sebagaimana telah direkam dan disistetisasi melalui olah algoritma perusahaan-perusahaan digital itu.
Data-perilaku-pengguna internet (user behavior data) ini mencakup jejak-jejak digital kita pernah berkomunikasi dengan siapa melalui internet, kita pernah membuka situs apa saja, kita pernah berbelanja apa saja secara online, kita pernah mencari informasi atau sumber apa saja di mesin pencari dan lain-lain. Data-perilaku-pengguna-internet inilah jantung dari bisnis media digital.
Data ini merupakan dasar dari apa yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama Facebook, Google, Amazon dan lain-lain yaitu pengembangan iklan digital tertarget, pengembangan produk-produk kecerdasan buatan dan pengembangan machine learning terus-menerus dan semakin paripurna.
Persoalannya data-perilaku-pengguna-internet ini hanya dikuasai dan dimanfaatkan secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan raksasa digital itu. Para pengguna internet tidak pernah sungguh-sungguh memiliki data yang mereka hasilkan sendiri.
Lebih dari itu, pemanfaatan data-perilaku-pengguna-internet itu lebih sering merugikan para pengguna internet sendiri. Pengguna internet menjadi sangat rawan diperlakukan sebagai sasaran pelanggaran privasi, pemerasan, operasi intelijen dan lain-lain. Dalam konteks inilah "the right to be forgotten" menjadi kesadaran dan tuntutan baru di Eropa sejak tahun 2006.
Hingga tahun 2018, ada lebih dari 2,8 juta pengguna internet di Eropa yang mengajukan penghapusan jejak-jejak digital kepada perusahaan penyedia layanan digital seperti Google dan Facebook.
Namun pelembagaan hak ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada aras kebebasan pers,kebebasan berpendapat dan berekspesi. Pelembagaan "the right to be forgotten" dianggap memunculkan ancaman sensor bagi media massa, serta dapat mereduksi potensi deliberasi media internet. UU ITE yang berlaku di Indonesia juga perlu dipersoalkan dalam konteks ini karena juga melembagakan the right to be forgotten.
Merujuk pada European Data Protection Directive, setidaknya ada empat lokus the right to be forgotten:
1.Penyebarluasan informasi melalui media jurnalistik online
2.Penyebarluasan informasi melalui media online non jurnalistik
3.Penyebarluasan informasi melalui search engine
4.Pengolahan dan penggunaan data perilaku pengguna search engine atau media sosial untuk periklanan digital.
Pertama, penyebarluasan informasi melalui media jurnalistik di Indonesia merujuk kepada UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. UU Pers telah mengatur perlindungan dan penghormatan atas privasi, sementara Pedoman Pemberitaan Media Siber lebih detail lagi mengatur kewajiban media untuk menghapus atau meralati berita yang tidak berimbang, menghakimi, mengancam keselamatan atau masa depan seseorang.
Pengaturan "the right to be forgotten" dalam UU ITE mesti merujuk kepada ketentuan ini. Titik tolaknya jelas sekali adalah, Kode etik Jurnalistik.
Dalam kerangka yang sama dapat ditegaskan bahwa berita negatif tentang seseorang, katakanlah pejabat publik yang menghadapi masalah korupsi, belum tentu berita yang salah. Berita negatif bisa jadi muncul karena subyek berita memang memiliki kelemahan atau kesalahan.
Sejauh media memberitakan berdasarkan fakta, mampu menjaga asas praduga tak bersalah, berdisiplin verifikasi dan bersikap hati-hati, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk mencabut atau menghapus berita negatif tentang seseorang.
Fungsi utama pers adalah pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan. Maka sudah pada tempatnya jika pers sering secara kritis memberitakan tindakan, perilaku dan keputusan pejabat publik. Sebaliknya, sudah seharusnya muncul kesadaran bahwa menjadi sasaran kritik pers adalah konsekuensi logis dari posisi jabatan publik, sejauh kritik dilakukan secara proporsional dan etis.
Dalam konteks inilah kita menemukan penjelasan mengapa regulasi tentang the right to be forgotten di Eropa memberikan pengecualian kepada media jurnalistik. Gugatan the right to be forgotten di Eropa tidak dapat diterapkan kepada media jurnalistik.
Masalahnya kita tidak menemukan pengecualian itu dalam UU ITE. Dalam undang-undang ini terkait dengan the right to be forgotten, posisi media jurnalistik disamakan dengan jenis media lain dalam kategori “Penyelenggara Sistem Elektronik”.
Kedua, penyebarluasan informasi pribadi melalui media online non jurnalistik menemui kendala belum adanya standard etis tentang arus informasi atau komunikasi digital, khususnya di media sosial. Secara umum the right to be forgotten dibedakan dengan hak atas privasi. Hak atas privasi merujuk kepada penyebaran informasi dalam skala terbatas, sementara the right to be forgotten merujuk kepada penyebaran informasi secara publik pada waktu tertentu.
Pembedaan ini sulit dioperasionalkan dalam media sosial karena facebook, blog, instagram dan lain-lain memeprlihatkan sebuah hibridasi antara mode komunikasi personal, kelompok, publik sekaligus massa.
Batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi kabur dalam media sosial. Perlu kehatihatian dan kejelian untuk menerapkan prinsip-prinsip the right to be forgotten untuk media sosial ini.
Ketiga, jika merujuk kepada Uni Eropa, regulasi tentang "the right to be forgotten" sesungguhnya lebih difokuskan kepada penyebarluasan informasi melalui search engine. Search engine seperti google umumnya tidak memproduksi informasi sendiri, tetapi mengagregasi informasi dari berbagai sumber, mengolah dan menyajikannya kembali dalam skala global.
Pertanyaannya adalah bagaimana menghapuskan informasi atau akses informasi yang terlanjut tersebar secara global? Hukum yang mana yang menjadi dasar? Faktanya, belum ada hukum internasional yang mengatur hal ini dan tidak ada sinkronisasi hukum antar negara tentang hal yang sama. UU ITE pun belum memperlihatkan antisipasi memadai atas persoalan ini.
Keempat, pengolahan dan penggunaan data perilaku pengguna search engine atau media sosial untuk kebutuhan periklanan digital dan pengembangan kecerdasan-buatan justru tidak menjadi focus pengaturan dalam UU ITE. Tanpa banyak disadari, penyedia layanan media sosial dan mesin pencari seperti facebook, google, youtube, twiter sebenarnya selalu ”memata-matai” para penggunanya.
Mereka merekam identitas diri, kebiasaan dan perilaku para penggunanya. Mereka menyediakan berbagai aplikasi digital, tetapi dengan aplikasi itu pula mereka mampu melacak kendaraan yang kita gunakan, di mana tempat tinggal kita, restauran yang sering kita kunjungi, barang yang kita koleksi, liburan yang kita dambakan, gangguan kesehatan kita dan seterusnya.
Data perilaku itu kemudian menjadi instrumen utama bisnis media digital, sebagai obyek aktivitas periklanan digital dan pengembangan kecerdasan-buatan. Inilah sebenarnya persoalan utama dalam isu the right to be forgotten saat ini. Hak para pengguna internet untuk menghapuskan jejak-jejak aktivitas digital mereka.
Hak untuk terbebas dari pengawasan dan pencatatan media sosial dan search engine. Pokok persoalan penting ini sepertinya justru luput dari perhatian. UU ITE lebih memfokuskan perhatian kepada perlindungan kepentingan pribadi dari penyebarluasan informasi melalui media massa dan media sosial seperti dijelaskan di atas.
*Agus Sudibyo, Head of New Media Research Center ATVI Jakarta.
Berita Terkait : Rata-rata orang Indonesia pakai 5GB per bulan
Berita Terkait : Persaingan era digital paksa akomodasi lokal tingkatkan daya saing
Berita Terkait : BPS: Penetrasi internet Indonesia berkembang pesat
Pewarta: Agus Sudibyo*
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2018